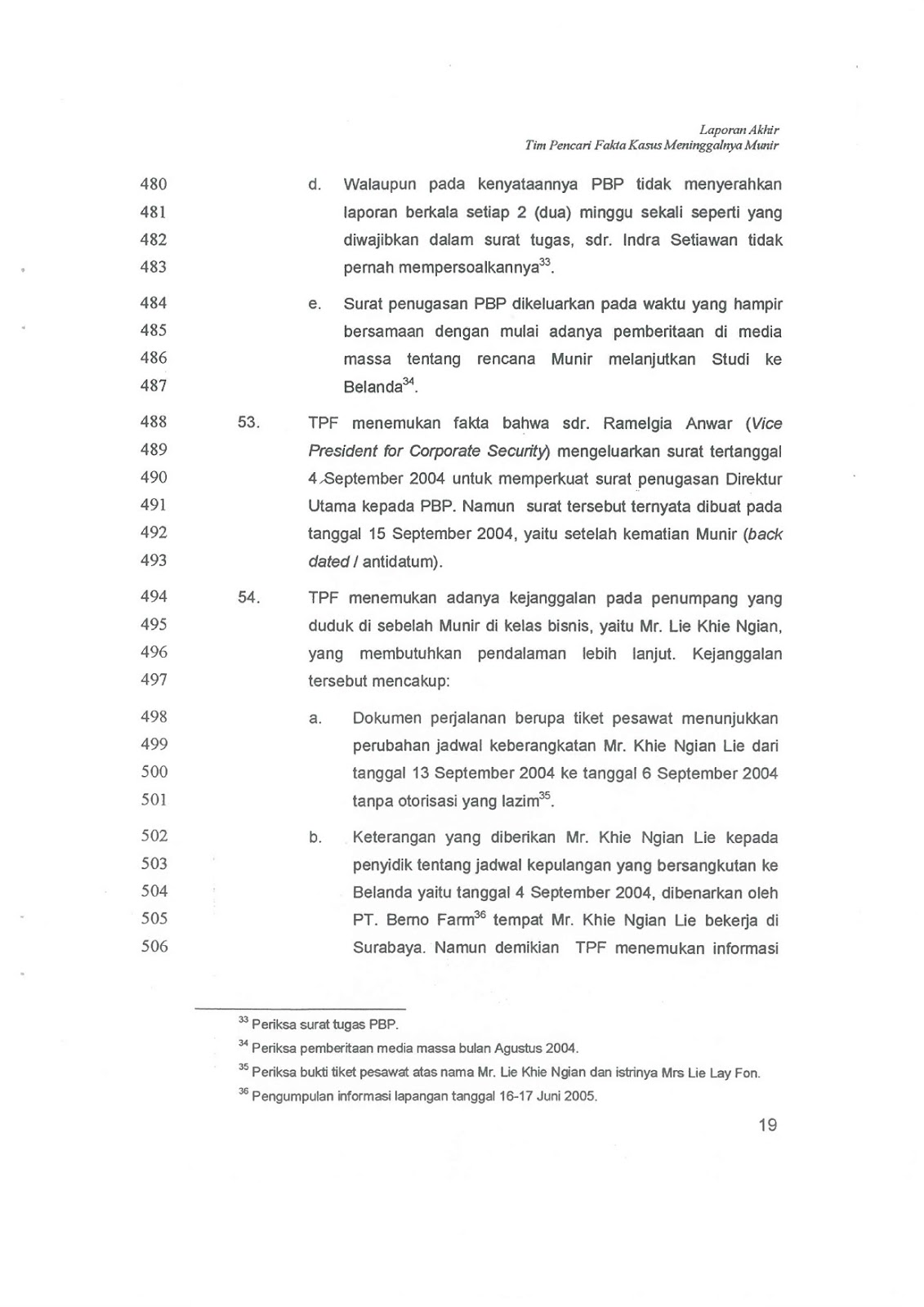Sumber gambar: http://www.activistpost.com/
Akhir-akhir ini di Indonesia memanas lagi
pembicaraan tentang ekstrimisme dalam agama, terutama agama Islam. Pengeboman
terhadap gereja masih terjadi, terakhir bom gereja di Samarinda. Hal itu
terjadi – entah secara kebetulan atau tidak – bersamaan dengan gelombang tuntutan
masyarakat Islam agar ditegakkan hukum pidana dalam kasus dugaan penodaan agama
yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jakarta.
Aksi massa yang di dalamnya terdapat berbagai
kelompok umat Islam tersebut dituduh sebagai bagian dari ekstrimisme, dan ada
yang menuduh sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah meski
akhirnya itu tidak terbukti.
Kasus penodaan agama memang sesuatu hal yang
tidak mudah untuk dipikirkan solusinya, sebab itu menyangkut psikologi massa,
adanya umat yang tersinggung perasaan keagamaannya. Saya juga menduga itu tak
lepas dari “rasa diperlakukan tidak adil sebagai kaum mayoritas yang
dikalahkan.” Jika dalam kasus seperti itu tak ada solusi hukum pidana, lantas
solusi yang bagaimana yang dapat mereparasi luka perasaan umat tersebut? Jika
Pasal 156 a KUHP dianggap ketentuan hukum yang bermasalah, lalu bagaimana cara
menyelesaikan perselisihan terkait perasaan sosial tersebut? Ini menjadi tugas
para terpelajar untuk memikirkannya, bukan sekedar tak suka dengan Pasal 156 a
KUHP tapi tak ada substitusi solusi yang lebih baik yang bisa diterima banyak
pihak. Harus diambil konsensus nasional untuk itu.
Dalam pembahasan artikel ini, saya tidak
menggunakan istilah radikalisme, tapi saya memilih istilah ekstrimisme.
Radikalisme berasal dari kata radical yang
artinya of or going to the root or origin; fundamental. Definisi yang selama ini dipakai adalah: radical is representing extreme forms of religious fundamentalism.
Saya tidak setuju dengan definisi
tersebut sebab fundamentalisme agama itu sepadan dengan puritanisme, di mana akar ajaran agama tidak dapat dipastikan
sebagai ajaran kekerasan, kecuali ajaran kekerasan terjadi dalam konteks
untuk melawan penindasan atau serangan para musuh.
Jadi,
pondasi dan akar ajaran agama dalam kondisi normal adalah bukanlah kekerasan
atau bukan ajaran ekstrimisme. Oleh sebab itu maka saya menggunakan istilah
ekstrimisme, yang berarti kelakuan atau tindakan ekstrim karena telah melampaui
atau menyimpang dari ajaran dasar dari agama itu sendiri.
Agama Sebagai Respon Terhadap Kekerasan
Mengapa
agama-agama tertentu mempunyai ajaran yang bernada keras? Agama Yahudi lahir
dari jaman Nabi Musa yang memimpin Bangsa Israel (Bani Israel), pada waktu itu
bangsa Israel diperbudak oleh rezim Firaun di Mesir. Musa menjadi nabi pada
tahun 1450 SM dengan tugas untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan yang
dilakukan oleh rezim Firaun. Pada jaman itu, pertarungan antar bangsa
sedemikian kerasnya.
Maka
Pada jaman Nabi Musa lahir pulalah ayat perang diantaranya Ulangan 20: 12-13
yang menentukan: “Tetapi jika kota itu
tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan bertempur melawan engkau, maka
haruslah engkau mengepungnya; dan setelah Tuhan, Allahmu, menyerahkannya ke
dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang
laki-laki dengan mata pedang.” Berarti dalam perang ini perempuan dan
anak-anak tidak boleh dibunuh.
Begitu
pula agama Kristen lahir sebagai respon atas penindasan dan kekerasan yang
dilakukan oleh imperialis Romawi yang bekerjasama dengan para pemuka Yahudi
yang menjadi kaki tangan penguasa Romawi. Maka saat itu lahirlah ayat
perlawanan diantaranya dalam Kitab Injil Matius ayat 10: 34 yang menyatakan, “Jangan anggap Aku datang membawa damai ke
bumi ini. Aku tidak datang membawa damai. Aku datang membawa pedang.”
Pun ketika Pandawa berperang melawan Kurawa, di
mana wangsa Pandawa yang ditindas, maka dalam Bhagavad Gita: Sloka 18.17 Sri Krishna menyatakan: “Orang yang tidak digerakkan oleh keakuan
palsu dan kecerdasannya tidak terikat, tidak membunuh, meskipun ia membunuh
orang di dunia ini. Ia juga tidak terikat oleh perbuatannya”. Artinya,
manusia tidak terikat oleh perbuatannya meskipun ia melakukan pembunuhan dalam
melawan angkara murka musuh-musuhnya. Ini sebagian ayat yang bermaksud
menggerakkan semangat Arjuna agar tidak ragu-ragu dalam membunuh musuh-musuhnya
dalam perang itu.
Barangkali hanya Budha yang
tak mempunyai ayat tentang kekerasan. Tetapi dalam Panchavudha-Jataka (Jataka-1
no. 55) dikisahkan perjalanan Bodhisatta yang pernah berusaha menyerang Yaksa (yang
sering membunuh manusia) dengan segala senjata yang dimiliki Sang Budha. Tetapi
semua senjatanya gagal untuk melukai atau mermbunuh Yaksa. Namun Yaksa menjadi
kagum atas keberanian Bodhisatta sehingga Yaksa yang jahat itu tunduk mengikuti
ajaran Budha. “Tanpa kemelekatan yang
menghalangi hati atau pikiran. Ketika kebenaran ditegakkan dengan damai untuk
memenangkan, Ia yang melakukan hal demikian, akan mendapatkan kemenangan, dan
semua belenggu musnah sama sekali.”
Agama Islam juga hadir di saat Jazirah Arab
mengalami kegelapan, para pria menindas kaum wanita, anak-anak perempuan
dibunuh karena tidak diharapkan kelahirannya, perang antar suku sering terjadi,
kejahatan merajalela, sehingga lahir Islam sebagai revolusi sosial yang
kemudian mengalami tekanan dan ancaman pembasmian sebab dianggap sebagai
ancaman kekuasaan pada waktu itu. Nabi Muhammad dan para pengikutnya harus
menyingkir ke Madinah karena menjadi target-target pembunuhan di Makkah.
Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad menyusun
kepemimpinan, membuat perjanjian dengan umat Yahudi untuk hidup bersama saling
melindungi. Namun ternyata tidak mudah, sebab ada saja kelompok-kelompok Yahudi
yang mengingkari perjanjian dengan melakukan serangan-serangan yang bahkan serangan-serangan
itu dibantu oleh kelompok-kelompok muslim munafik.
Umat Islam seringkali mengalami serangan
sehingga turun pula Surat At Taubah ayat 123 yang menyatakan, “Hai orang-orang beriman, perangilah
orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu dan hendaklah mereka merasakan
kekerasan darimu.” .Ayat ini sebagai perintah keberanian untuk melawan kaum
nonmuslim yang selalu menyerang umat Islam.
Agama memang muncul dalam
revolusi-revolusi sosial dalam merespon penindasan-penindasan panjang yang
terjadi. Jika dikatakan bahwa ajaran-ajaran agama – seperti halnya ajaran suatu
ideologi – merupakan sumber-sumber legitimasi internal masing-masing dalam
melakukan kekerasan, sebenarnya kekerasan yang dimaksudkan bukanlah dalam
kondisi sosial yang normal, tetapi kekerasan dalam arti perlawanan dalam
merespon penindasan-penindasan.
Secara fundamental atau
akarnya, ajaran Islam dapat dilihat ketika Nabi Muhammad membuat perjanjian
damai dengan umat nonmuslim dengan prinsip saling melindungi, mengharamkan harta,
darah dan kehormatan umat nonmuslim. Artinya, umat Islam diharamkan merebut
harta nonmuslim, diharamkan menganiaya dan membunuh umat nonmuslim dan dilarang
menyerang kehormatan mereka.
Tetapi agama juga
mengajarkan respon terhadap serangan musuh. Terkait dengan respon terhadap imperialisme
dan penindasan-penindasannya, ajaran agama terbukti menjadi sumber kekuatan
perlawanan yang hebat. Prof. Daniel C. Maguire, pakar etika di Amerika Serikat
mengistilahkan agama sebagai sacred
energy yang mampu mengubah dunia dan melawan kekuatan “agama terkejam”,
yakni kapitalisme. Meskipun ternyata dalam kenyataannya dalam sejarahnya banyak
pemuka agama yang berselingkuh dengan para imperialis kapitalis, yang hal itu
merupakan kecelakaan dalam praktik teologis.
Sejarah Eropa Abad Kegelapan
merupakan contoh buruk peran agama yang justru menipu masyarakat, turut
menghisap masyarakat, sehingga lahirlah gerakan dan ideologi sekularisme yang
kapok melihat persekutuan antara agama dengan negara-negara monarki pada jaman
itu. Trauma sejarah itu berbekas hingga sekarang, melahirkan doktrin pemisahan
agama dengan negara yang dianut oleh kaum sekularis hingga sekarang.
Lahirnya Ekstrimisme
Djamaludin Ancok dari Fakultas Psikologi
Universitas Gadjah Mada dalam risetnya membeberkan relasi psikologis antara
radikalisme dengan ketidakadilan, termasuk ketidakadilan dalam pembentukan
opini dunia. Ia menyatakan, “Pemberian
label yang sangat buruk pada Islam dan Rezim Islam yang berseberangan dengan
kepentingan Barat dengan menggunakan istilah: Poros setan, Agama teroris, Agama
barbar, Agama kekerasan, Islam agama berdarah-darah. Sementara kegiatan di
negara beragama Kristen (negara di Amerika Selatan) yang melawan rezim Barat
tidak pernah dilabel seperti itu. Menuduh pesantren sebagai sumber pengembangan
terorisme di berbagai negara Islam, dan ingin mengganti kurikulum yang lebih
akseptabel di mata pihak Barat. Mereka tidak melihat berapa banyak orang-orang
keluaran pesantren yang tidak terlibat terorisme dan menjadi tokoh yang
menonjol anti kekerasan, dan pendukung setia pihak Barat.”
Pakar perdamaian dunia, Johan Galtung, menguraikan
akar-akar kekerasan secara lebih luas, dari masalah-masalah pembangunan dan
primordialisme dalam pertarungan peradaban di mana bangsa-bangsa di dunia ini
masing-masing berusaha menunjukkan eksistensi sebagai bangsa unggul. Dunia
menjadi spiral kekerasan sejak lama, sehingga ekstrimisme Islam bukan sebagai
fenomena baru yang eksis tanpa bersambung dengan sejarah dan masa lalu.
Kaum terpelajar juga pasti sudah mengetahui
realitas bahwa kehancuran negara-negara Timur Tengah yang berpenduduk mayoritas
muslim adalah akibat politik minyak dan doktrin National Security Amerika Serikat. Timur Tengah menjadi wilayah “permainan”
tempat uji coba senjata-senjata baru dari luar Timur Tengah serta wilayah
perebutan sumber daya minyak. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa kendaraan
berteknologi energi listrik sulit berkembang, padahal sudah layak untuk
dipergunakan? Jawabnya adalah tentang kekuasaan mafia minyak yang masih harus
menghabiskan jatah keserakahan minyaknya.
Lalu apakah keadaan yang buruk, penindasan
dan penistaan kemanusiaan tersebut tidak akan berakibat apa-apa? Jika semua
manusia itu bisa dibuat bodoh dan penurut maka tak ada satupun pembalasan.
Tentu saja akan terjadi pembalasan-pembalasan yang tergetnya juga menyasar
kepada orang-orang tak bersalah. Tapi bagi para teroris pembalas itu,
masyarakat yang diam melihat penindasan-penindasan yang tak terukur
kekejamannya, itu dianggap telah memberikan legitimasi terhadap
kekejaman-kekejaman struktural modern itu. Di situ dalil agama bisa menjadi
pembakar kebencian dan dendam.
Oleh sebab itulah maka upaya-upaya de-ekstrimisasi
dengan pendidikan-pendidikan tanpa dibarengi dengan pendidikan-pendidikan
penyadaran kepada para states terrorist
yang menyalahgunakan hukum internasional itu, hanya merupakan upaya-upaya
pemadaman api-api kecil saja. Api besarnya tetap menyala. Belum lagi permainan jaringan
politik internasional antar negara yang sepaham yang melakukan “pemeliharaan
teroris” untuk alasan kepentingan mereka. Sebagai contoh, kasus Irak yang
dituduh sebagai tempat penyimpanan senjata pemusnah massal, ternyata tuduhan
itu fiktif. Setelah Irak hancur, tak pernah ditemukan senjata pemusnah massal yang
digosipkan dengan menggunakan hukum internasional itu. Kasus peledakan Menara
Kembar WTC yang kontroversial yang kemudian dijadikan alasan untuk pembasmian
teroris di dunia dengan mengacak-acak Timur Tengah.
Jika ditelaah sejarah dunia secara umum, ekstrimisme
sebenarnya timbul sebagai reaksi terhadap keadaan, terutama terhadap
ketidakadilan. Kita pasti masih ingat apa sebutan bagi para pejuang kemerdekaan
Indonesia yang dilontarkan oleh penjajah Belanda, yakni “kaum ekstrimis”. Kaum
ekstrimis ini dalam sudut pandang bangsa Indonesia adalah kaum pejuang, yang
memang juga menggunakan cara-cara kekerasan dengan melakukan serangan-serangan
mematikan dalam perang terbuka ataupun gerilya. Pemerintah Hindia Belanda
menyebut itu sebagai tindakan kaum ekstrimis yang memberontak kepada rezim yang
sah.
Lalu apakah terorisme dan ekstrimisme di
dunia akan bisa berakhir? Rupanya sulit, sebab ini tidak seperti peristiwa saling
teror antara kekuasaan Katholik dan Protestan di Eropa pada Abad ke-17 yang
dapat diakhiri dengan kesadaran bersama dengan Perjanjian Westphalia tahun
1648. Pada saat terjadi kekerasan antar pemeluk agama Kristen di Eropa, banyak
di antara mereka orang Kristen Eropa yang lari mengungsi ke Timur Tengah dan
dilindungi oleh negara Islam (Kekaisaran Ottoman) serta diberikan kebebasan
menjalankan ibadah agamanya.
Terorisme saat ini terjadi dalam pertarungan
antara Grand Terrorist melawan
musuh-musuhnya yang disebut sebagai para teroris (little terrorist), di mana banyak kaum terpelajar dunia yang
memperoleh sokongan dana-dana pendidikan, humanisme (kedok) dan proyek-proyek riset
untuk penguasaan sumber daya alam dari para grandmaster
of terrorist itu. George Soros dalam pengantar buku Escaping The Resource Curse menyatakan bahwa perang saudara di
Afrika termasuk akibat campur tangan korporasi-korporasi migas yang
menginginkan dan memperoleh konsesi-konsesi dengan cara menyogok para penguasa.
Soros juga memberi contoh lainnya, pada tahun
1951, Mohammed Mossadeq dari Iran menasionalisasi Anglo-Iranian Oil Company.
Akibatnya, dia dijungkalkan melalui sebuah kudeta yang dirancang badan
intelijen AS, CIA. Tapi, 20 tahun kemudian gelombang nasionalisasi telah
menyapu negara-negara produsen minyak utama dunia, sehingga menyebabkan krisis
minyak global pertama. Sejak saat itu, kekuatan tawar menawar telah bergeser kepada
negara-negara produsen minyak. Pemerintahan nondemokratis lalu bisa bergantung
pada penerimaan dan dukungan dari pemerintah negara-negara pengonsumsi minyak.
Inilah yang menjadi elemen penting dari lambannya perkembangan demokrasi di
Timur Tengah. Jadi, benarlah bahwa negara-negara Timur Tengah menjadi hancur
satu persatu akibat proyek para teroris besar yang berbentuk
korporasi-korporasi migas di negara-negara maju di Amerika dan Eropa.
Tetapi yang dilakukan oleh kaum terpelajar sekuler
hanyalah mengutuk-ngutuk para little terrorist-nya,
dan yang jelas mereka sungkan untuk mengutuk para majikannya yang menjadi grandmaster of terrorist. Artinya,
kampanye antiterorisme tidak menyentuh pelaku-pelaku besarnya, tapi kampanye
itu justru didanai oleh para pelaku besar terorisme.
Upaya-upaya yang selama ini dilakukan
hanyalah upaya “penundukan” dalam doktrin-doktrin Hak Asasi Manusia (HAM), di
mana tidak semua orang mau tunduk. Dominasi penghasilan dunia, yakni sekitar 80
persen penghasilan dunia dikuasai oleh sekitar 20 persen penduduk dunia selaku
para orang kaya, melawan 80 persen penduduk dunia yang tertindas, tak akan
pernah membuat seluruh dari 80 persen penduduk dunia itu tunduk kepada
doktrin-doktrin para penindas yang disebarkan melalui rayuan para kaum
terpelajar.
Tapi jika kaum terpelajar di seluruh dunia
mau bersatu memaksa dihentikannya teror-teros besar termasuk berupa dominasi
oleh 20 persen orang kaya itu, maka teroris yang kecil-kecil akan akan bisa
jauh berkurang, sebab tak ada lagi alasan fundamental untuk berjihad dengan “hukum
perang.”